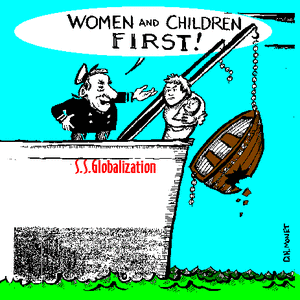
Globalisasi Berdampak Baik atau Buruk bagi Kehidupan Kelompok Perempuan Oct 26, '07 12:49 AM
for everyone
Globalisasi Berdampak Baik atau Buruk bagi Kehidupan Kelompok PerempuanÒ
Adzkar AhsininÓ
Pembuka
Fenomena globalisasi secara terminologis dapat dimaknai sebagai intensifikasi relasi-relasi sosial seluas dunia yang menghubungkan lokalitas-lokalitas berjauhan sedemikian rupa sehingga peristiwa di satu tempat ditentukan oleh peristiwa lain yang terjadi bermil-mil jaraknya dari tempat tersebut dan sebaliknya.[1] Terminologi ini menekankan karakteristik khusus globalisasi yang menjadi ruang hidup manusia modern yang ditandai oleh keluasan (extencity), kekuatan (intencity), kecepatan (velocity), dan dampak (impact) yang luar biasa dan yang belum terbayangkan sebelumnya.[2] Fenomena globalisasi dipicu oleh kemajuan industri, teknologi informasi, dan transportasi sehingga limitasi jarak kini bukan menjadi hambatan (borderless). Jika ditilik dari sisi ini globalisasi seakan-akan menjadi hukum alam, namun jika ditilik sisi sosiologis fenomena globalisasi seperti halnya fenomena sosial lainnya, pada dirinya terkandung paradoksal dan ambivalensi.
Paradoks dan ambivalensi ini terlihat manakala fenomena ini ditempatkan pada tataran relasi-relasi antarindividu dan relasi-relasi antarnegara yang telah direduksi hanya pada dimensi ekonomi. Dominasi karakteristik ekonomi pada fenomena globalisasi inilah yang semestinya perlu dicermati karena kini telah berkembang menjadi isme yang dikenal dengan sebutan neoliberalisme.
Pada awalnya, neoliberalisme pertama-tama bukan urusan ekonomi, tetapi suatu proyek filosofis yang beraspirasi menjadi teori komprehensif tentang manusia dan masyarakat. Dengan kata lain neoliberalisme suatu bangunan ideologi tentang manusia dan pengaturan masyarakat. Namun relasi-relasi kultural, politik, legal, sosial, psikologis, estetik, spiritual, dan lainnya ditopang oleh transaksi laba rugi yang berlaku dalam kinerja ekonomi pasar. Kemudian, neoliberalisme diproyeksikan sebagai desain kerangka normatif tentang bagaimana manusia dan tata masyarakat harus menjadi melalui: pertama, dengan proyek normatif memandang semua relasi manusia sebagai relasi pasar, neoliberalisme mengajukan sosok homo eoconomicus sebagai teori kodrat manusia dalam semua bidang kehidupan manusia. Kedua, setiap manusia perlu mengubah dirinya sesuai idiom pasar dan bisnis. Artinya setiap apa saja yang melekat padanya adalah modal (capital) yang mesti diubah menjadi laba. Ketiga, karena setiap manusia dipandang sebagai homo eoconomicus, maka kemiskinan disebabkan kesalahan manusia itu sendiri. Kemiskinan bukan masalah sosial, melainkan kegagalan mengubah asset diri menjadi laba. Solusinya bukan social welfare, tetapi individual self-care. Keempat, sesudah homo eoconomicus menjadi model perilaku manusia, maka Pemerintah juga harus dirubah menjadi pemerintah ekonomi (economic government). Negara/pemerintah sebagai perusahaan adalah idiom khas neoliberal. Perubahan ini membutuhkan landasan hukum melalui hukum yang mengatur aspek-aspek tata Negara (hukum tata Negara). Kelima, perentangan prinsip pasar merambah tidak hanya pada bidang-bidang yang secara tradisional bukan wilayah ekonomi, tetapi juga menciptakan cabang serta ranting transaksi-transaksi baru yang sudah ada. Dengan kata lain dari suatu proses transaksi pasar diciptakan beberapa subtransaksi, kemudian dikembangkan berbagai sub-sub transaksi lain. Melalui proses ini muncul apa yang disebut ekonomi maya dengan buihnya yang sama sekali tidak punyai kaitan apapun dengan perkembangan ekonomi sektor riil.[3]
Pilar-Pilar Neoliberalisme dan Pelaku Neoliberalisme
Neoliberalisme sebagaimana diuraikan dimuka bertujuan menata setiap aspek kehidupan berdasarkan prinsip dan kalkulasi ekonomi. Bagaimana ideology ini kemudian tersebar dan dianut oleh hampir seluruh negara-negara berkembang yang terkena krisis. Jika dirunut kebelakang, neoliberalisme dihasilkan melalui Washington Consensus yang digagas oleh dua lembaga multilateral, yakni IMF dan Bank Dunia, serta Pemerintah AS. Washington Consensus pada awalnya merupakan konsep yang didesain sebagai upaya untuk menanggulangi krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Latin pada dasawarsa 1980-an dan 1990-an. Namun kemudian konsep ini pada akhirnya diterapkan pada negara-negara berkembang lain yang terkena krisis. Pada dasarnya Washington Consensus terdiri dari sepuluh elemen, yang meliputi:
*
Disiplin fiskal, pemerintah disarankan untuk melakukan kebijakan fiscal yang konservatif di mana defisit anggaran tidak boleh lebih dari dua persen terhadap PDB.
*
Perlu adanya prioritas bagi pengeluaran publik dalam anggaran pemerintah. Pemerintah harus berusaha untuk memperbaiki distribusi pendapatan melalui belanja pemerintah.
*
Reformasi pajak, pemerintah perlu memperluas basis pemungutan pajak.
*
Liberalisasi finansial, sektor ini perlu didorong lebih liberal agar terjadi peningkatan efisiensi.
*
Kebijakan nilai tukar yang memiliki kredibilitas yang menjamin terdorongnya iklim persaingan.
*
Mendorong liberalisasi perdagangan dengan cara menghilangkan restriksi-restriksi kualitatif (larangan-larangan) secara progresif.
*
Mendorong kompetisi antara perusahaan domestik dan asing sehingga meningkatkan efisiensi.
*
Melakukan program privatisasi melalui pengalihan kepemilikan perusahaan milik Negara kepada swasta.
*
Iklim deregulasi harus didorong untuk menghilangkan restriksi masuk pasar sehingga pasar semakin kompetitif.
*
Pemerintah harus melindungi hak kekayaan intelektual. [4]
Kesepuluh elemen ini kemudian diekstrasikan menjadi tiga pilar utama neoliberalisme, yakni liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi.
Neoliberalisme sebagai sebuah ideology, eksistensinya akan terus berkelanjutan apabila ia menjadi sebuah sistem yang operasional. Sebagai sebuah sistem perlu ditopang peraturan.-peraturan. Peraturan-peraturan ini dikembangkan oleh institusi internasional yang memiliki visi mengkodifikasi dan membentengi tiga kebebasan fundamental neoliberalisme:
1.
Kebebasan sirkulasi modal
2.
Kebebasan perdagangan atas barang dan jasa
3.
Kebebasan investasi[5]
Pada titik ini hukum ekonomi internasional kemudian dikembangkan untuk melegalkan kebebasan fundamental ini. Bahkan diciptakan pula mekanisme pengadilan internasional untuk mengadili negara-negara yang dipandang menghambat laju dan gerak neoliberalisme.[6]
Selain membutuhkan peraturan, agar ideology neoliberal dapat dianut dan menjadi norma-norma yang mencakup seluruh tatanan kemasyarakatan maka membutuhkan pelaku-pelaku (agency). Terdapat institusi-institsusi yang selama ini dikenal sebagai agen neoliberalisme:
1.
Lembaga keuangan multilateral: (i) Bank Pembangunan Multilateral yang terdiri dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Regional (Bank Pembangunan Asia, Bank Pembangunan Afrika, Bank Pembangunan Eropa, Bank Pembangunan antarAmerika, dan Bank Pembangunan Islam)[7] dan (ii) Dana Moneter Internasional (IMF)[8]
2.
Praktisi Bisnis Internasional (perusahaan multi nasional/MNC)
3.
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)[9]
4.
Lembaga Kredit Ekspor (ECA)[10]
5.
Negara-negara G7
Faktor pendukung lain yang perlu mendapatkan catatan penting adalah, neoliberalisme selain bertumbuh dengan subur dengan ditopang oleh kultur ideology konsumtif.[11]
Bagaimana Neoliberalisme Masuk ke Indonesia
Awal embrio neoliberalisme berkecambah dalam locus habitus Indonesia manakala Pemerintah Republik Indonesia mulai berhutang kepada negara/institusi kreditur baik secara bilateral maupun multilateral dan masuknya Indonesia menjadi anggota lembaga keuangan internasional. Utang bilateral Indonesia dengan negara kreditur dimulai sejak tahun 1946 berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 1946 tentang Pinjaman Nasional yang diubah melalui UU Nomor 9 Tahun 1946. Utang luar negari yang dibuat dengan berlandasankan pada undang-undang berlangsung hingga tahun 1958. Namun setelahnya sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno tahun 1966 tidak diketemukan dokumen pengesahan perjanjian luar negeri, baik melalui undang-undang maupun Keputusan Presiden. Kemudian dalam era Presiden Soeharto utang luar negeri yang dibuat dari tahun 1968 hingga masa pemerintahan Presiden Soeharto, pengesahan perjanjian utang luar negeri dimuat dalam Keputusan Presiden, namun sebagian besar dari perjanjian utang luar negeri tidak dilegalkan sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku.[12]
Keanggotaan Indonesia dalam IMF dan IBRD[13] dimulai pada tahun 1954 berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1954 tentang Keanggotaan RI pada IMF dan IBRD. Namun, pada 1966 Indonesia menarik diri dari keanggotan kedua organisasi melalui UU Nomor 1 Tahun 1966. Menurut undang-undang ini penarikan diri tersebut berlaku surut hingga 17 Agustus 1965. Penarikan diri ini terkait dengan kebijakan Presiden Seokarno keluar dari PBB pada 1 Januari 1965. Kemudian berdasarkan pada 8 November 1966 Indonesia kemali menjadi anggota IMF dan IBRD melalui UU Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali RI dalam IMF dan IBRD. Selain itu, pada 17 Juni 1968 berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1968 Indonesia menjadi anggota IDA (International Development Association).[14] Meskipun telah menjadi anggota IMF, IBRD sejak tahun 1967 dan IDA sejak tahun 1968 tidak diketemukan satu pun dokumen yang mengesahkan perjanjian utang antara Pemerintah dengan ketiga lembaga tersebut. Namun demikian tidak berarti bahwa Pemerintah tidak memiliki utang kepada lembaga-lembaga tersebut. Sejak Juni 1974 hingga Desember 2006 Pemerintah telah menandatangani perjanjian utang dengan IBRD sebanyak 370 perjanjian, sedangkan perjanjian utang yang telah ditandatangani dengan IDA berjumlah 73 perjanjian yang dibuat sejak September 1968 hingga Desember 2006Kemudian, ikatan perjanjian utang luar negeri antara Pemerintah dengan IMF baru terjadi pada 31 Oktober 1997 manakala Indonesia mengalami krisis ekonomi dengan jumlah utang sebesar US$ 7,3 milyar.[15]
Pemberian utang inilah yang pada akhirnya menempatkan Indonesia di bawah control kekuasaan lembaga-lembaga keuangan ini karena setiap pinjaman diikuti kondisionalitas yang harus dipatuhi. Kondisionalitas ini yang dikenal dengan program penyesuaian struktural (SAP) yang mencakup kebijakan-kebijakan pengurangan peran pemerintah peran pemerintah, liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi. IMF mensyaratkan bahwa Pemerintah Indonesia harus melaksanakan kebijakan dan program yang ditentukan sebagaimana dituangkan dalam Memorandum of Economic and Financial Policies (MEFP) atau dikenal dengan nama Letter of Intent (LoI). IMF merekomendasikan kepada Pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan sebuah paket program reformasi ekonomi sebagai bagian dari penyesuaian ekonomi makro Indonesia.[16] Sekurang-kurang terdapat sekitar 23 LoI dan MEEP yang dibuat sejak tahun 1997 hingga akhir tahun 2003.
Sebagaimana IMF yang memberikan paket stand by loan, Bank Dunia ikut pula dalam program penyelamatan ekonomi Indonesia dengan mengucurkan paket Structural Adjustment Loan (SAL)[17] dan program reformasi kebijakan (Policy Reform Support Loan/ PRSL I dan II). Demikian pula halnya Asian Development Bank (ADB). [18] Negara-negara G7 tidak ketinggal pula memanfaatkan situasi keterpurukan kondisi perekonomian Indonesia dengan paket pemberian utang, misalnya Jepang melalui Miyazawa Plan, dan Amerika Serikat.[19] Sebelumnya, menjelang awal tahun 1970-an, atas kerjasama dengan World Bank, IMF, dan ADB dibentuk suatu konsorsium Inter-Government Group on Indonesia (IGGI) yang terdiri atas sejumlah negara industri maju untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Melalui konsorsium ini setiap tahun Indonesia mengajukan utang luar negeri baru untuk menutupi defisit anggaran. Defisit anggaran selain ditutup dengan utang luar negeri, juga berasal dari penjualan aset-aset negara melalui privatisasi.
Sebenarnya paket kebijakan yang menjadi kondisionalitas utang luar negeri tersebut merupakan pintu masuk bagi pelaku-pelaku bisnis internasional untuk merealisasikan kepentingannya. Dengan demikian jejak neoliberalisme juga perlu dilihat dari ditetapkannya undang-undang yang memberikan kemudahan investasi yang diintervensi oleh kekuatan modal pelaku-pelaku bisnis internasional. Undang-undang ini akan menjadi sumber legitimasi operasionalisasi pelaku-pelaku bisnis internasional dalam melakukan investasinya di Indonesia.
Syarat ini dikemukakan Milton Friedman yang menyatakan bahwa hukum sangat penting bagi neo-liberalisme karena hukum pada dasarnya merefleksikan otoritas negara sebagai regulator. Pada posisi ini terlihat ambivalensi dan paradoksnya neoliberalisme, di satu sisi neo-liberalisme menginginkan agar negara tidak ikut campur dalam arus perdagangan barang dan jasa antar-negara. Namun di sisi lainnya, negara diharapkan ikut serta dalam memberikan aturan-aturan yang memudahkan liberalisasi perdagangan. [20] Di titik inilah kemudian muncul upaya-upaya untuk mempengaruhi negara sebagai pembuat hukum agar mengakomodasi kepentingan pelaku-pelaku bisnis internasional.
Tunas kekuasaan pelaku bisnis internasional mengemuka pada tahun 1967, manakala PT. Freeport McMorran mulai mengeksplorasi dan mengeksploitasi tambang di Papua. Investasi tersebut diberikan alas hukum oleh Pemerintah RI melalui UU Penanaman Modal Asing. Kemudian diikuti penetapan UU Penanaman Modal Dalam Negeri. Lebih jauh lagi agar dikenal sebagai negara perusahaan, Pemerintah menciptakan undang-undang yang ditujukan untuk mengundang pengusaha menanamkan investasinya. Pada akhirnya apa yang melekat dan dimiliki oleh Negara Indonesia baik tanah, sumber daya alam, dan tenaga kerja ditransaksikan secara ekonomis sehingga melahirkan UU tentang Kehutanan, UU tentang Pertambangan, UU Ketenagakerjaan, dan masih banyak undang-undang lain yang mengatur aspek-aspek ekonomi.[21]
Dampaknya Terhadap Kehidupan Perempuan
Beralihnya fungsi pemerintah sebagai pemegang kewajiban pemenuhan social welfare menjadi tanggung jawab individu (self-care) berdampak marginalisasi kelompok-kelompok rentan seperti kelompok perempuan, kelompok anak, kelompok miskin, dan kelompok rentan lainnya.[22] Marjinalisasi ini dikarenakan kelompok rentan ini tersingkir tidak saja oleh kinerja prinsip daya beli menentukan jaminan penikmatan hak, tetapi juga oleh penghapusan jaring pengaman sosial.[23] Fenomena komodifikasi melalui mekanisme pasar layanan sosial mendasar seperti pendidikan, kesehatan, permukiman, air bersih, pangan yang kini terjadi merupakan bukti empiris marjinalisasi kelompok rentan. Kondisi ini diperparah dengan politik kebijakan anggaran publik yang menghilangkan subsidi layanan sosial mendasar dan subsidi lain yang dibutuhkan untuk menopang kehidupan warga negara. Doktrin neoliberal menganggap alokasi anggaran tersebut dianggap membuang sumber finansial secara cuma-cuma yang sebenarnya bisa dialokasikan ke sektor lain yang lebih menguntungkan dan berpotensi mengakumulasi peningktan keuntungan ekonomis.
Dampak sistem ekonomi neoliberal terhadap pengalaman perempuan dalam perspektif feminisme berbeda satu perempuan dengan perempuan yang lain. Oleh karenanya dalam menganalisis dampak tersebut harus berangkat dan merujuk dari pengalaman perempuan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai feminisme yang menitikberatkan pada pengetahuan dan pengalaman individu perempuan. [24]
Seiring dengan fenomena globalisasi, muncul feminisme global guna menjawab penindasan terhadap perempuan akibat dari kebijakan dan praktik-praktik globalisasi. Feminisme global menekankan bahwa penindasan terhadap perempuan di satu bagian dunia seringkali disebabkan oleh apa yang terjadi di bagian dunia yang lain.[25] Charlotte Bunch mengidentifikasi 2 (dua) tujuan jangka panjang feminisme global :
1.
Hak setiap perempuan atas kebebasan memilih, dan kekuatan untuk mengendalikan hidupnya sendiri di dalam dan di luar rumah. Memiliki kekuasaan atas hidup dan tubuh perempuan sendiri merupakan hal yang esensial untuk memastikan adanya rasa kebanggaan dan otonomi pada setiap perempuan
2.
Penghapusan semua bentuk ketidakadilan dan penindasan dengan menciptakan tatanan sosial dan ekonomi yang lebih adil secara nasional dan internasional. Hal ini berarti keterlibatan perempuan dalam perjuanagan kebebasan nasional, dalam perencanaan pembangunan nasional, dan perjuangan bagi perubahan di tingkat lokal dan global.[26]
Persoalan keperempuanan dalam konstruksi neoliberalisme muncul ketika Structural Adjusment Program (SAP) yang diadopsi oleh IMF dan Bank Dunia mempengaruhi kehidupan keseharian perempuan. Paket SAP diterapkan diberbagai negara dengan salah satu fokus utamanya memotong uang belanja publik untuk menyeimbangkan anggaran pemerintah dan hutang paling dirasakan oleh kelompok perempuan. Desai memberi argumentasi bahwa SAP telah mempengaruhi perempuan secara mendunia sebab pengaturan tersebut telah membuat peranan perempuan banyak berubah dari kemungkinan perempuan menjadi produser menjadi nonproduser, dan biaya krisis yang diambil dana alokasi untuk layanan sosial mendasar mengakibatkan lagi keterpurukan perempuan.[27]
Oleh karenanya untuk melihat dampak neoliberalisme dalam kehidupan kelompok perempuan, maka terdapat pertanyaan kunci yang sangat mendasar yakni hak-hak asasi perempuan apa yang hilang atau dilanggar sebagai dampak dianutnya ideologi neoliberalisme oleh negara. Pertanyaan kunci ini membutuhkan parameter untuk mengeksaminasi sejauhmana sistem ekonomi neoliberal berdampak pada kehidupan kelompok perempuan. Instrumen hukum HAM internasional dapat dijadikan sebagai alat analisis untuk mempersoalkan ketidakadilan neoliberalisme secara lebih substansial.
Dalam konteks merespon kebutuhan spesifik kelompok perempuan hukum internasional menciptakan instrumen hukum HAM internasional yang dikenal dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW). Instrumen hukum ini membebankan negara sebagai pemegang kewajiban utama untuk memastikan bahwa seluruh hak-hak yang dijamin di dalamnya dihargai, dilindungi, dan dipenuhi melalui pembuatan peraturan-peraturan yang tepat di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya sehingga setiap individu perempuan dapat menikmati HAM dan kebebasan pokoknya atas dasar persamaan dengan laki-laki. Dengan demikian apakah politik kebijakan anggaran public memenuhi hak asasi perempuan dapat dilihat adakah alokasi anggaran yang ditujukan secara spesifik untuk menjamin dinikmati hak asasi yang melekat pada setiap individu perempuan seperti yang tercantum dalam CEDAW. Namun hal yang perlu mendapatkan catatan penting, instrument ini seperti halnya instrument hukum HAM internasional utama yang lain, masih menempatkan negara sebagai pelaku pelanggaran HAM dan sekaligus pemegang kewajiban untuk menjamin perlindungan dan penikmatan HAM, belum memasukkan pelaku non negara. Dengan demikian pelaku-pelaku neoliberal tidak dapat dituntut pertanggungjawaban selayaknya negara dalam konteks perlindungan dan pemenuhan HAM.
Kemudian selain analisis anggaran, analisis terhadap substansi peraturan perundang-undangan yang mengandung spirit neoliberalisme signifikan dilakukan guna membongkar akar ketertindasan kelompok perempuan. Terkait dengan perspektif feminisme, maka untuk melihat substansi peraturan perundang-undangan berperspektif feminis atau tidak dapat mempergunakan pisau analisis Feminist Legal Theory. Feminist Legal Theory menyangkut dua aspek yakni teori hukum berperspektif feminis dan praktik hukum berperspektif feminis. Teori hukum berperspektif feminis membantu memetakan persoalan-persoalan yang terkait dengan adanya kebutuhan untuk menangani persoalan yang menyangkut hak-hak perempuan di hadapan hukum. Karakteristik dasar teori hukum berperpektif feminis yang dapat dijadikan pijakan untuk melakukan perubahan substansi hukum meliputi : (i) mengubah pandangan bahwa hukum adalah sesuatu yang netral dan obyektif; (ii) mengidentifikasi implikasi hukum yang justru melanggengkan relasi subordinatif terhadap perempuan; (iii) bagaimana hukum itu bekerja dalam konteks yang lebih luas. Sedangkan praktik hukum yang berperspektif femisnis menitikberatkan pada 2 (dua) fokus: pertama, bagaimana hukum mempengaruhi perempuan dan menyumbangkan penindasan terhadap mereka. Kedua, bagaimana hukum digunakan untuk meningkatkan posisi sosial perempuan. Kemudian jika substansi hukum neoliberal dianalisis dengan perspektif feminist legal theory maka perspektif ini dapat dipergunakan untuk mengeksaminasi sampai sejauhmana substansi tersebut berpihak pada perempuan atau malah menyumbang terjadinya subordinasi terhadap perempuan. Dalam kerangka ini maka analisis proses pembentukan hukum perlu dilakukan karena pada dasarnya hukum merupakan produk politik di mana menjadi arena kontestasi aneka kepentingan.

0 komentar:
Posting Komentar